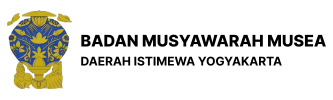oleh Dr. Ir. Yustinus Suranto, M.P.
Perintis dan Pengembang Kajian Kayu Budaya Nusantara
Sambungan…
- Taksonomi Tetumbuhan
Sebagaimana disebutkan, bahwa taksonomi tetumbuhan dapat dipolakan melalui penerapan ilmu taksonomi yang dalam hal ini adalah ilmu taksonomi tetumbuhan. Ilmu taksonomi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pemilahan secara hirarkial makhluk hidup dan pengelompokkan makhluk hidup itu menjadi takson-takson atau peringkat-peringkat. Masing-masing takson atau peringkat itu mencakupi takson lain atau peringkat lain yang aras tingkatannya pada posisi yang lebih rendah.
Secara hirarkhial, setiap takson dari aras yang tertinggi sampai dengan aras yang terrendah itu diberi nama dengan terma tertentu. Terma tertentu yang disematkan pada masing-masing aras yang tertinggi menuju ke aras yang terrendah ini meliputi: kerajaan (kingdom), devisi (devisio) atau pilum (phyllum), kelas (Classis), ordo, famili (familia), genus, spesies, dan varietas. Dengan demikian, terdapat delapan aras takson di dalam khasanah taksonomi.
Dalam perspektif ilmu taksonomi ini, seluruh makhluk hidup dibedakan menjadi enam kerajaan. Di antara keenam kerajaan itu, ada dua kerajaan makhluk hidup yang terpenting dipandang dari perspektif Material Budaya. Kedua kerajaan itu adalah kerajaan tetumbuhan (Kingdom of Plantae) dan Kerajaan Binatang (Kingdom of Animalia). Takson Kerajaan Tetumbuhan dan takson Kerajaan Binatang ini memiliki nilai terpenting karena kedua takson ini merupakan sumber utama material budaya. Berkenaan dengan konteks tulisan yang berfokus pada Kayu Budaya ini, maka takson Kerajaan Binatang sebagai material budaya tidak akan disajikan di sini. Penyajian tertuju sepenuhnya pada Kerajaan Tetumbuhan.
Dalam konteks taksonomi tetumbuhan, seluruh tetumbuhan itu dikelompokkan menjadi empat devisio, yakni: (1) Thalophyta, (2) Bryophyta, (3) Pteridophyta, dan (4) Spermatophyta. Thalophyta merupakan tetumbuhan yang berpenampilan sebagai lumut. Bryophyta merupakan tetumbuhan yang berpenampilan berupa jamur. Pteridophyta merupakan tetumbuhan yang berpenampilan pepakuan. Spermatophyta merupakan tetumbuhan yang bersperma. Dengan demikian, tetumbuhan Spermatophyta ini melakukan proses ovulasi yang kemudian disebut Penyerbukan. Oleh karenanya, tetumbuhan ini memiliki organ-organ penyerbukan yang berupa bunga, yang kemudian bertumbuh menjadi buah dan biji. Di antara keempat devisio ini, Spermatophyta berposisi sebagai devisio yang terpenting dalam konteks kayu budaya.
Oleh karena itu, maka Spermatophyta ditelusuri tingkatan pengelompokannya lebih lanjut sampai pada tingkatan jenis (species). Penelusuran dan contoh jenis tetumbuhan disajikan pada sub-bab berikut. - Pengelompokan dan Jenis Tumbuhan
Devisio Spermatophyta dibedakan lebih lanjut menjadi dua kelompok kelas (Classis) berdasarkan penampilan buahnya, yaitu (1) tetumbuhan yang berbiji terbuka, dan (2) tetumbuhan yang berbiji tertutup. Tetumbuhan berbiji terbuka mencakup ordo Coniferales. Ordo Coniferales dibagi lagi lebih lanjut menjadi tiga familia, yaitu familia-familia: Pinaceae, Araucariaceae, dan Podocarpaceae.
Pinaceae mencakup beberapa genus. Salah satu di antaranya adalah genus Pinus. Genus ini memiliki jenis yang disebut Pinus merkusii (Pinus). Kata “Pinus” yang berada di dalam kurung itu merupakan nama jenis yang diberikan di dalam khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, jenis ini bernama Pinus dalam konteks bahasa Indonesia.
Sementara itu, familia Araucariaceae mencakup banyak genus. Salah dua di antaranya adalah genus Araucaria dan genus Agathis. Genus Araucaria memiliki jenis yang disebut Araucaria araucana (Araucaria), sedangkan genus Agathis memiliki jenis yang disebut Agathis loranthifolia (Damar).
Podocarpaceae mencakup beberapa genus. Salah satu di antaranya adalah genus Podocarpus. Genus Podocarpus memiliki jenis yang bernama Podocarpus levis (Podokarpus).
Demikian pengelompokan dan jenis tetumbuhan Spermatophyta yang berbiji terbuka. Uraian berikutnya berfokuskan tentang Spermatophyta yang berbiji tertutup.
Berdasarkan jumlah keping penyusun bijinya, Spermatophyta yang berbiji tertutup ini dibedakan lebih lanjut menjadi dua kelompok, yaitu (1) kelompok tetumbuhan yang bijinya berkeping satu, dan (2) kelompok tetumbuhan yang bijinya berkeping dua. Kelompok tetumbuhan berkeping satu ini secara keseluruhan disebut Monocotyledoneae, sedangkan Kelompok tetumbuhan berkeping dua secara keseluruhan disebut Dicotyledoneae. Kata “Monocotyledoneae” sering disingkat menjadi kata “Monokotil”, sedangkan Kata “Dicotyledoneae” disingkat dengan kata “Dikotil”. Uraian tentang Spermatophyta Berbiji Tertutup yang Monokotil ini disajikan pada sub-bab berikut. - Spermatophyta Berbiji Tertutup yang Monokotil
Monokotil dalam konteks kayu budaya mencakup dua familia, yakni Poaceae dan Arecaceae. Familia Poaceae mencakup beberapa sub-familia, salah satu sub-familia itu adalah Bambusoideae. Sub-familia ini mencakup empat genus, yaitu genus: Bambusa, Dendrocalamus, Giganthochloa, dan Schizotachum.
Genus Bambusa memiliki banyak jenis. Beberapa jenis di antaranya adalah Bambusa vulgaris (Bambu kuning), Bambusa bamboos (Bambu hitam), Bambusa spinosa (Bambu duri), dan Bambusa vulgaris (Bambu ampel).
Genus Dendrocalamus memiliki banyak jenis. Dua jenis di antaranya adalah Dendrocalamus asper (Bambu betung), Dendrocalamus strictus (Bambu peting).
Genus Giganthochloa memiliki banyak jenis. Empat jenis di antaranya adalah Giganthochloa apus (Bambu apus), Giganthochloa verticillata (Bambu legi), Giganthochloa atter (Bambu hitam / Bambu wulung), dan Giganthochloa hasskarliana (Bambu lengka). Sementara itu, genus Schizotachum juga memiliki banyak jenis. Satu jenis di antaranya adalah Schizotachum blumei (Bambu wuluh).
Berdasarkan uraian di atas, maka Poaceae pada jalur sub-familia Bambusoideae ini merupakan kelompok tetumbuhan tertentu. Kelompok tetumbuhan ini secara bersama disebut kelompok Perbambuan.
Setelah menyajikan familia Poaceae, maka pada gilirannya untuk menyajikan tetumbuhan Monokotil yang terfokus pada familia Arecaceae. Penyajiannya dikemas dalam uraian berikut.
Familia Arecaceae ini mencakup 5 sub-familia, yakni sub-familia: Arecoideae, Ceroxyloideae, Coryphoideae, Nypoideae, dan Calamoideae. Uraian terhadap masing-masing sub-familia ini disajikan secara berurutan sebagai berikut.
Pertama adalah sub-familia Arecoideae. Arecoideae mencakup dua genus yakni genus Areca dan genus Cocos. Satu contoh jenis pada Areca adalah Areca pinanga (Pinang). Sementara itu, salah satu contoh jenis pada genus Cocos adalah Cocos nucifera (kelapa).
Kedua adalah sub-familia Ceroxyloideae. Ceroxyloideae mencakup genus Metroxylon. Salah satu species yang tercakup dalam genus Metroxylon adalah Metroxylon sago (sagu).
Ketiga adalah sub-familia Coryphoideae. Coryphoideae mencakup genus Arenga. Salah satu species tercakup dalam genus Arenga ini adalah Arenga pinnata (Aren). Bijinya disebut di dalam khasanah Bahasa Jawa disebut “Kawung”.
Keempat adalah sub-familia Nypoideae. Nypoideae mencakup genus Nypa. Salah satu species tercakup dalam genus Nypa adalah Nypa fruticans (Nipah).
Kelima adalah sub-familia Calamoideae. Calamoideae mencakup kelompok rotan. Beberapa jenis rotan disajikan di sini, yakni: Rotan manau, Rotan sega, Rotan sega air, Rotan balukbuk, Rotan irit, Rotan Batu, Rotan Lilin, dan Rotan jermasin.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pada Familia Arecaceae ini, maka sub-familia pertama sampai dengan keempat merupakan kelompok tetumbuhan yang memiliki batang dalam posturnya yang tegak. Kelompok tetumbuhan berbatang ini secara keseluruhan disebut Pepaleman. Batang tegaknya secara umum disebut “Gelugu”.
Sementara itu, di dalam Familia Arecaceae pada sub-familia yang kelima yakni Calamoideae, maka terlihat bahwa Calamoideae ini merupakan kelompok tetumbuhan yang batangnya tumbuh secara menjalar dan menanjat. Penanjatannya dilakukan dengan memanfaatkan tetumbuhan lain yang berbatang tegak. Batang tegak milik tetumbuhan lain ini diperankan olehnya sebagai perancah atau pendukung pemanjatannya. Sifat pertumbuhan yang menjalar dan memanjat yang demikian ini disebut Liana. Kelompok tetumbuhan liana ini secara keseluruhan disebut “Rerotanan”. Batangnya yang menjalar itu secara umum disebut “Rotan”.
Demikianlah uraian tentang tetumbuhan Monocotyledoneae. Uraian berikut berkait dengan Dycotyledoneae atau kelompok tetumbuhan yang bijinya berkeping dua. Kata Dycotyledoneae sering disingkat menjadi kata Dikotil. Uraiannya disajikan sub-bab sebagai berikut. - Spermatophyta Berbiji Tertutup yang Dikotil
Tetumbuhan yang berkeping dua mencakup amat banyak jumlah familia. Tetumbuhan dikotil ini tumbuh mendominasi kawasan Nusantara. Dalam konteks kayu budaya Nusantara, maka dipilih tujuh familia yang sangat penting untuk disajikan di sini. Ketujuh familia ini meliputi familia: Dipterocarpaceae, Fabaceae, Moraceae, Rutaceae, Santalaceae, Sapotaceae, dan Verbenaceae. Satu per satu familia ini disajikan secara berurutan sebagai berikut.
Familia Dipterocarpaceae mencakup sangat banyak jenis. Jenis-jenis tersebut antara lain: Shorea sp. (Meranti), Dipterocarpus sp. (Kapur), Dryobalanops lanceolata (Kamper) dan Hopea mengarawan (Bangkirai). Jenis-jenis ini tumbuh secara dominan di Kawasan Pulau Kalimantan.
Familia Fabaceae yang bersinonim dengan Leguminoceae itu mencakup sangat banyak jenis. Dua jenis yang mewakilinya untuk disajikan di sini adalah Paraserianthes falcataria (Sengon) dan Rhynchocarpa monophylla (Tesek).
Familia Magnoliaceae mencakup banyak jenis. Dua jenis di antaranya adalah Michelia alba (Cempaka putih) dan Michelia champaka (Cempaka kuning).
Familia Moraceae juga mencakup banyak jenis. Dua di antaranya adalah Ficus benzamina (Beringin) dan Ficus religiosa (Bodi).
Familia Rutaceae mencakup banyak jenis. Satu jenis yang sangat terkenal adalah Murraya paniculata (Kemuning).
Familia Santalaceae mencakup banyak jenis. Satu jenis yang paling terkenal adalah Santalum album (Cendana).
Familia Sapotaceae mencakup banyak jenis. Dua di antaranya yang populer di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Manilkara kauki (Sawo kecik) dan Mimusop elengi (Tanjung).
Familia Verbenaceae mencakup banyak jenis. Dua jenis di antaranya yang sangat terkenal adalah Tectona grandis (Jati) dan Vitex pubescens (Laban).
Secara keseluruhan, tetumbuhan Dikotil merupakan kelompok tetumbuhan yang berbatang tegak dan memiliki percabangan yang intensif, baik berupa dahan, cabang, anak cabang, ranting, dan anak ranting. Kelompok tetumbuhan ini secara keseluruhan disebut “Pepohonan”. Batang utama yang tegak dan bebas cabang itu secara umum disebut “Balak”. - Morfologi Tetumbuhan
Sebagaimana telah disajikan, bahwa tetumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok yakni tumbuhan yang buahnya memiliki biji yang terbuka dan biji yang tertutup. Tetumbuhan yang berbiji tertutup itu dibedakan lebih lanjut menjadi monokotil dan dikotil.
Berdasarkan penampilan postur tubuhnya, maka tetumbuhan monokotil memiliki habitus yang dikarakterkan oleh adanya batang tunggal. Batang tunggal ini tanpa disertai oleh dahan. Sebagaimana diketahui, dahan berstatus sebagai percabangan tingkat pertama pada batang pokok. Pada Familia Poaceae sub-familia Bambusoideae, batang utama ini disebut “Bambu”.
Sementara itu, pada Familia Arecaceae, khususnya pada keempat sub-familia, yakni Arecoideae, Ceroxyloideae, Coryphoideae, dan Nypoideae, maka terbukti bahwa batang utamanya berdiri tegak. Batang utama ini secara keseluruhan disebut “Gelugu”. Kelompok tetumbuhan ini secara bersama-sama disebut “Pepaleman”.
Di lain pihak, pada Familia Arecaceae dengan sub-familia Calamoideae, batang utama yang pertumbuhan bersifat menjalar atau liana ini disebut “Rotan”. Kelompok tetumbuhan ini secara bersama-sama disebut “Rerotanan”.
Setelah menelusuri habitus tetumbuhan monokotil, kini pada gilirannya untuk menelusuri habitus tetumbuhan dikotil. Penelusuran terhadap tetumbuhan dikotil akan disertai secara serentak oleh penelusuran terhadap kelompok tetumbuhan yang berbiji terbuka. Hasilnya diuraikan dalam paragraf berikut.
Dikotil merupakan kelompok tetumbuhan yang berbatang utama tunggal yang sifatnya berdiri tegak. Batang utama ini memiliki percabangan, baik berupa dahan, cabang, anak cabang, ranting, dan anak ranting. Pola percabangannya mengakibatkan tetumbuhan ini berpenampilan tertentu, yang secara keseluruhan membentuk tajuk. Tajuk ini bentuknya sangat bervariasi, yakni ada yang berbentuk menyerupai payung, silinder, dan pagoda.
Sementara itu, kelompok tetumbuhan yang berbiji terbuka merupakan tetumbuhan yang berbatang utama yang bersifat tunggal dan berdiri tegak. Meski demikian, batang utama ini tidak memiliki percabangan berupa dahan, tetapi hanya berupa cabang kecil, ranting, dan anak ranting saja. Secara keseluruhan, arsitektur tetumbuhannya berbentuk postur tajuk yang berbentuk kerucut.
Postur tetumbuhan yang dimiliki oleh kelompok tetumbuhan yang berbiji terbuka dan kelompok tetumbuhan dikotil ini secara keseluruhan disebut Pepohonan. Batang utamanya merupakan batang tunggal yang tegak. Batang tegak yang bebas dari percabangan ini, yakni batang yang segmennya dimulai dari permukaan tanah sampai dengan titik percabangan dahan, maka secara umum disebut “Balak”.
Dengan uraian di atas, maka dipahami bahwa tetumbuhan itu terkelompok secara garis besar menjadi empat kelompok habitus, yakni Perbambuan, Rerotanan, Pepaleman, dan Pepohonan. Secara berurutan, batang pokok pada masing-masing habitus tetumbuhan ini disebut “Bambu”, “Rotan”, “Gelugu”, dan “Balak”. Masing-masing secara berurutan dalam khasanah Bahasa Inggris disebut Bamboo, Rattan, Palm trunk, dan Log.
Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sejak awal kegiatan merintis dan mengembangkan bidang ilmu kayu budaya dan kebudayaan kayu pada tahun 1986, maka terbukti bahwa batang utama yang dihasilkan dari keempat kelompok tetumbuhan yang masing-masing disebut “Bambu”, “Rotan”, “Gelugu”, dan “Balak” ini semuanya merupakan material budaya yang digunakan pada kebudayaan tradisional. Oleh karena masing-masing material ini dihasilkan dari kelompok tetumbuhan yang berbeda secara taksonomis, maka sangat menarik untuk melakukan pengamatan terhadap komponen-komponen kimiawi yang berperan sebagai bahan utama penyusun masing-masing material ini. Hasil pengamatan disajikan dalam sub-bab Analisis Kimiawi Material Budaya Tradisional berikut. - Analisis Kimiawi Material Budaya Tradisional
Analisis secara kimiawi terhadap bambu, rotan, gelugu, dan balak sebagai material budaya tradisional ini telah dilakukan. Kegiatan analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui komponen kimiawi penyusun masing-masing material tersebut.
Hasil analisis memperlihatkan, bahwa masing-masing kelompok material budaya itu memiliki komponen kimia yang sama. Komponen itu meliputi: selulosa, lignin, hemiselulosa, ekstraktif, dan mineral. Dengan demikian, baik Bambu, Rotan, Gelugu, dan Balak itu terdiri atas komponen kimia yang sama, yakni selulosa, lignin, hemiselulosa, ekstraktif, dan mineral.
Berdasarkan proporsinya, maka komponen selulosa dan lignin menempati posisi dan proporsi yang dominan. Oleh karena itu, maka material budaya ini disebut sebagai bahan yang berlignoselulosa. Kata “Lignoselulosa” itu bersinonim dengan kata “Kayu”. Dalam terma kekinian, kata “Kayu” yang bersinonim dengan kata “Lignoselulosa” itu kemudian disebut dengan kata “Ligna”. Penggunaan kata “Ligna” dilakukan dalam kerangka ekonomisasi kata, karena huruf penyusun kata “Ligna” ini jelas berjumlah sedikit saja sehingga lebih pendek dan lebih hemat. Di samping itu, kata “Ligna” juga lebih mudah untuk dilafalkan oleh lidah masyarakat yang berkebudayaan modern.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa keempat material budaya tradisional itu memiliki komponen kimia yang sama. Kesemuanya merupakan bahan yang berkayu. Meskipun demikian, kebudayaan modern telah melakukan okupasi dan hegemoni terhadap makna material budaya tradisional tersebut. Fenomenanya disajikan dalam sub-bab berikut. - Okupasi Makna Kayu
Sebagaimana disebutkan dalam sub-bab Evolusi Kebudayaan bahwa kebudayaan berevolusi dari budaya pengumpul sampai dengan kebudayaan industri. Masyarakat berkebudayaan tradisional menggunakan Bambu, Rotan, Gelugu, serta Balak sebagai sumber kayu untuk diolah sebagai material budaya. Semua sumber kayu itu digunakan untuk berkarya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kayu atau lignoselulosa yang berasal dari Bambu, Rotan, Gelugu, dan Balak ini dimanfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik pada kebutuhan tingkat sederhana maupun pada kebutuhan yang kompleks. Dalam kebutuhan yang sederhana, semisal memerlukan kayu sebagai bahan bakar, maka kayu tersebut diambil dari semua sumber, baik Perbambuan, Rerotanan, Pepaleman, maupun Pepohonan. Dengan demikian, Bambu, Rotan, Gelugu, maupun ranting dan percabangan pada Balak ini digunakannya sebagai kayu bakar. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan yang kompleks, semisal membangun rumah adat, masyarakat tradisional juga menggunakan seluruh jenis sumber daya alam tersebut, baik Bambu, Rotan, Gelugu, dan Balak.
Sementara itu, masyarakat berkebudayaan modern yang secara evolutif mengada pada era waktu yang lebih belakangan dibandingkan dengan masyarakat berkebudayaan tradisional itu justru telah melakukan okupasi tentang makna kayu. Kayu atau Ligna yang makna semulanya mencakup semua material budaya, yakni Bambu, Gelugu, dan Rotan serta Balak itu, kemudian dipersempit cakupannya dan hanya ditujukan kepada Balak saja.
Dalam konteks Indonesia, kebudayaan modern yang dijadikan pola hidup masyarakat industri, maka terlihat bahwa sikap mengokupasi yang demikian itu dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 (Presiden Republik Indonesia, 2007). Melalui peraturan perundangan tersebut, maka kebudayaan modern mengeluarkan secara paksa Bambu, Rotan, dan Gelugu tersebut dari khasanah keaslian dan kesejatiannya. Masyarakat industrial ini kemudian mengkategorikan ketiganya sebagai material “Bukan Kayu”.
Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa masyarakat industri telah mempersempit dan merampas makna sejati kayu. Makna sejati kayu ini disematkan secara eksklusif melulu hanya kepada Balak saja. Dengan kata lain, Kayu sebagai sebuah identitas dan jati diri ini hanya ditahbiskan bagi Balak saja. Sebaliknya, Bambu, Rotan, dan Gelugu itu dikeluarkan dari khasanah kayu, meskipun secara kesejatian, ketiganya berintikan lignoselulosa atau ligna atau kayu. Dengan demikian, Bambu, Gelugu, dan Rotan yang kesemuanya adalah Ligna itu tidak diberi hak lagi untuk disebut Kayu.
Tindakan okupasi dan eksklusifikasi makna kayu ini menghadirkan konsekuensi negatif tertentu terhadap Bambu, Rotan, dan Gelugu. Konsekuensi negatif ini antara lain mengakibatkan deplesi atau ketunaan bagi ketiganya, baik dalam hal ketersediaannya maupun penggunaannya. - Penutup
Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas bahwa makna orisinal yang dirumuskan berdasarkan komponen kimiawi yang berupa Lignoselulosa atau Ligna atau Kayu itu sangat logis untuk disematkan pada keempat kelompok material budaya, yakni Bambu, Rotan, Gelugu, dan Balak. Dengan kata lain, seluruh material budayawi baik berupa Bambu, Rotan, Gelugu, dan Balak itu secara inklusif tercakup dalam terma “Kayu Budaya”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa materi yang dihasilkan oleh keempat kelompok tetumbuhan itu tercakup sebagai “Kayu Budaya”.
Dengan latar belakang uraian di atas, maka pada bagian akhir tulisan ini akan diarahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Nanang Dwinarto. Nanang Dwinarto yang berkarya pada Museum Monumen Jogja Kembali ini mengajukan pertanyaan secara tertulis dalam WAG Sahabat Barahmus dan Museum DIY pada 1 September 2024. Pertanyaannya dirumuskan sebagai berikut: “Bambu yang di dalam bahasa Jawa disebut Empring ini, apakah sama ataukah tidak sama dengan Kayu?”.
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tersedia dalam dua alternatif, yaitu alternatif (1) Bambu adalah sama dengan Kayu, dan alternatif (2) Bambu tidak sama dengan Kayu. Alternatif mana yang akan dinyatakan sebagai jawaban yang benar itu bergantung pada perspektif dan sudut pandang serta konteks yang digunakan untuk menjawabnya. Apabila menggunakan perspektif dan sudut pandang Kayu Budaya, maka jawaban yang benar adalah alternatif pertama, yakni bahwa Bambu adalah sama dengan Kayu. Sebaliknya, apabila menggunakan perspektif dan sudut pandang Kayu Industri, maka jawaban yang benar adalah alternatif kedua, yakni bahwa Bambu tidak sama dengan Kayu.
Penulis berharap semoga para pembaca budiman/wati lebih mengutamakan untuk menempatkan diri pada khasanah Kayu Budaya daripada menempatkan diri pada khasanah Kayu Industri. Semoga semesta pun mendukungnya. Salam Budaya Nusantara.
Sumber Pustaka
Anonimus, 2024.a. Charles-Darwin. https://www.britannica.com/biography/Charles-Darwin/The-Beagle-voyage. diakses pada 3
September 2024.
Anonimus, 2024.b. Out_of_Africa. https://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa. Diakses pada 4
September 2024.
Anonimus, 2024.c. Koentjaraningrat. https://en.wikipedia.org/wiki/Koentjaraningrat. Diakses pada 5
September 2024.
Anonimus, 2024.d. James-Watt. https://www.britannica.com/biography/James-Watt.
Diakses pada 5 September 2024.
Presiden Republik Indonesia, 2007. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/6TAHUN2007PP.HTM. Diakses pada 6
September 2024.